Ada masa ketika satu kata bisa menjatuhkan takhta.
Satu kalimat bisa membuat pengkhianat tak hanya kehilangan gelar, tetapi juga warisan, darah, bahkan nama di batu nisan.
Itulah sapatha, sumpah yang bukan sekadar janji, tapi kutukan abadi yang pernah mengguncang jantung Sriwijaya.
Palembang, UpdateKini – Di Seminar Hasil Kajian Koleksi Museum Sriwijaya, yang digelar di UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya (TWKS), Gandus, Palembang, Rabu (9/7/2025), suara para pemikir menggali makna dari prasasti-prasasti tua yang menyimpan sumpah dan kutuk, Sapatha.
Kata itu bukan sekadar bahasa, melainkan napas kekuasaan kuno. Bukan hanya ancaman, tapi cermin bagi jiwa-jiwa yang memegang amanah.
Di hadapan para pencinta sejarah, Dr. Dedi Irwanto, sejarawan dari Universitas Sriwijaya, mengisahkan bahwa sapatha bukan hanya cap batu dalam prasasti, tetapi jejak ideologi yang mengalir dari Sriwijaya ke zaman kini.
Ia menyebut sapatha sebagai penanda zaman yang terus hidup, dari zaman datu hingga ruang-ruang pemerintahan hari ini. Dalam suara paraunya, ia bertutur tentang sumpah yang kini menjelma dalam ikrar jabatan, menjadi pelita tanggung jawab yang tak terlihat namun terasa.
Bagi Dedi, sapatha mengandung rasa takut, bukan karena teksnya, melainkan karena kepercayaan yang tertanam dalam darah sejarah. Ketika seorang manusia menerima kekuasaan, katanya, ia juga menerima kemungkinan kutuk yang mengintai di balik pengkhianatan terhadap amanah.
“Integritas dan komitmen menjadi kunci utama dalam mengemban amanah,” tegasnya.
Namun tidak semua kutuk membawa murka. Dalam kejernihan keyakinan Buddha, Dedi menyampaikan tentang mereka yang hidup benar, yang wajahnya menjadi syarira, cahaya dari tubuh dan pikiran yang murni. Sapatha pun bisa menjadi berkah, bukan sekadar bayangan hukuman.
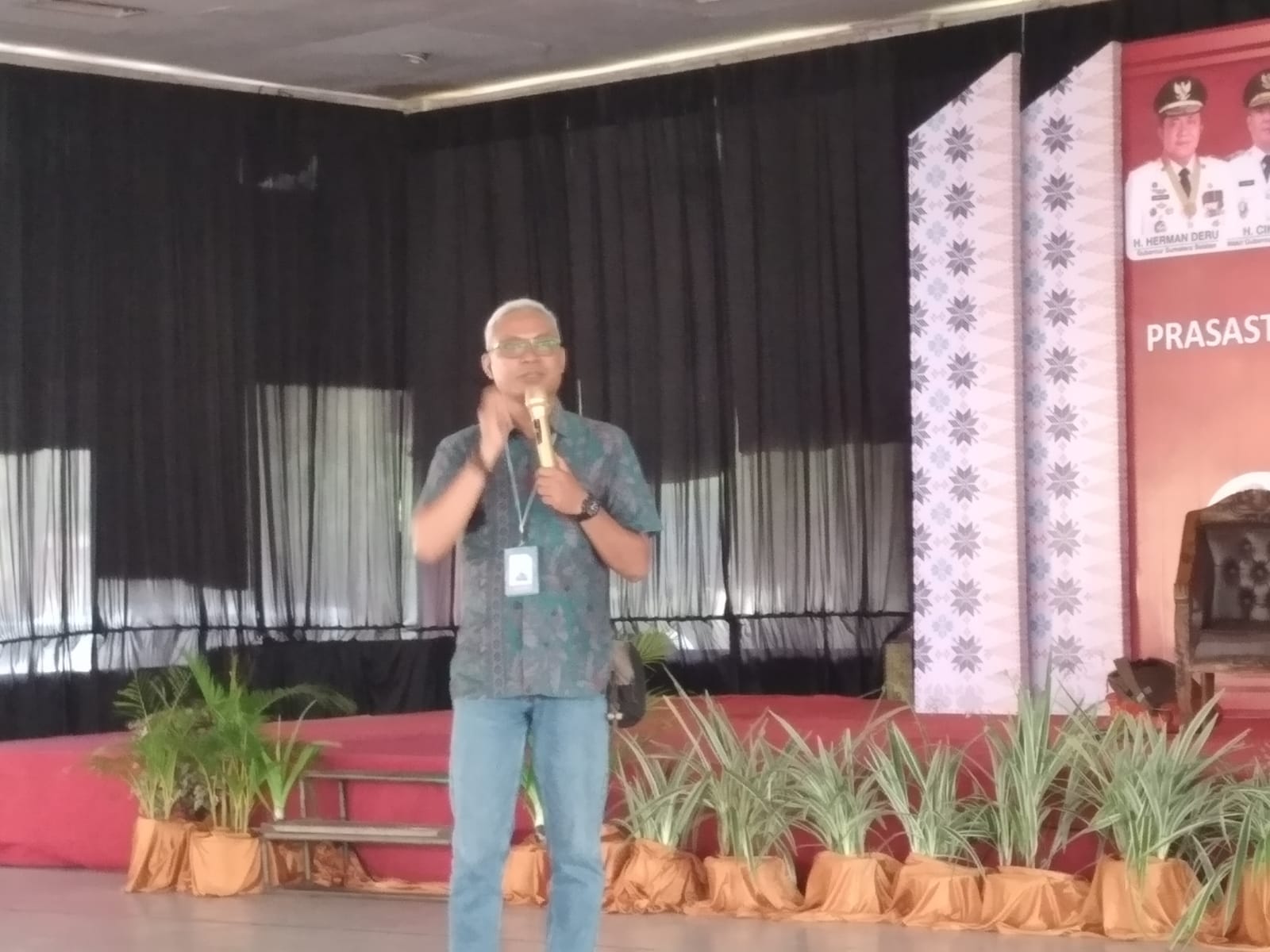
Sementara, Peneliti ahli muda BRIN sekaligus Ketua Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia (PAEI), Wahyu Rizky Andhifani, memaparkan bahwa sapatha di Sriwijaya merupakan instrumen politik sakral.
Perancangannya bukan hanya untuk melindungi kekuasaan datu, tetapi juga untuk menanamkan ketundukan total melalui kutukan yang bersifat kolektif dan transenden.
“Kutukan dalam sapatha tidak hanya menimpa pelaku pembangkangan, tapi juga keturunannya. Ini menunjukkan bentuk hukuman yang menghapus identitas sosial-politik seseorang secara menyeluruh,” ujarnya.
Menurut Wahyu, pelanggaran terhadap datu bukan sekadar anggapan melawan negara, tetapi sebagai dosa kosmik yang mengganggu keseimbangan spiritual. Konsekuensinya pun mistis seperti, sakit, kegilaan, kematian, bahkan kejatuhan moral.
“Sapatha membuktikan bahwa jalannya kekuasaan Sriwijaya tidak hanya lewat administrasi dan militer, tetapi juga melalui sistem hukum performatif, di mana kata-kata menjadi alat kendali dengan kekuatan metafisik yang hidup dalam prasasti,” lanjutnya.
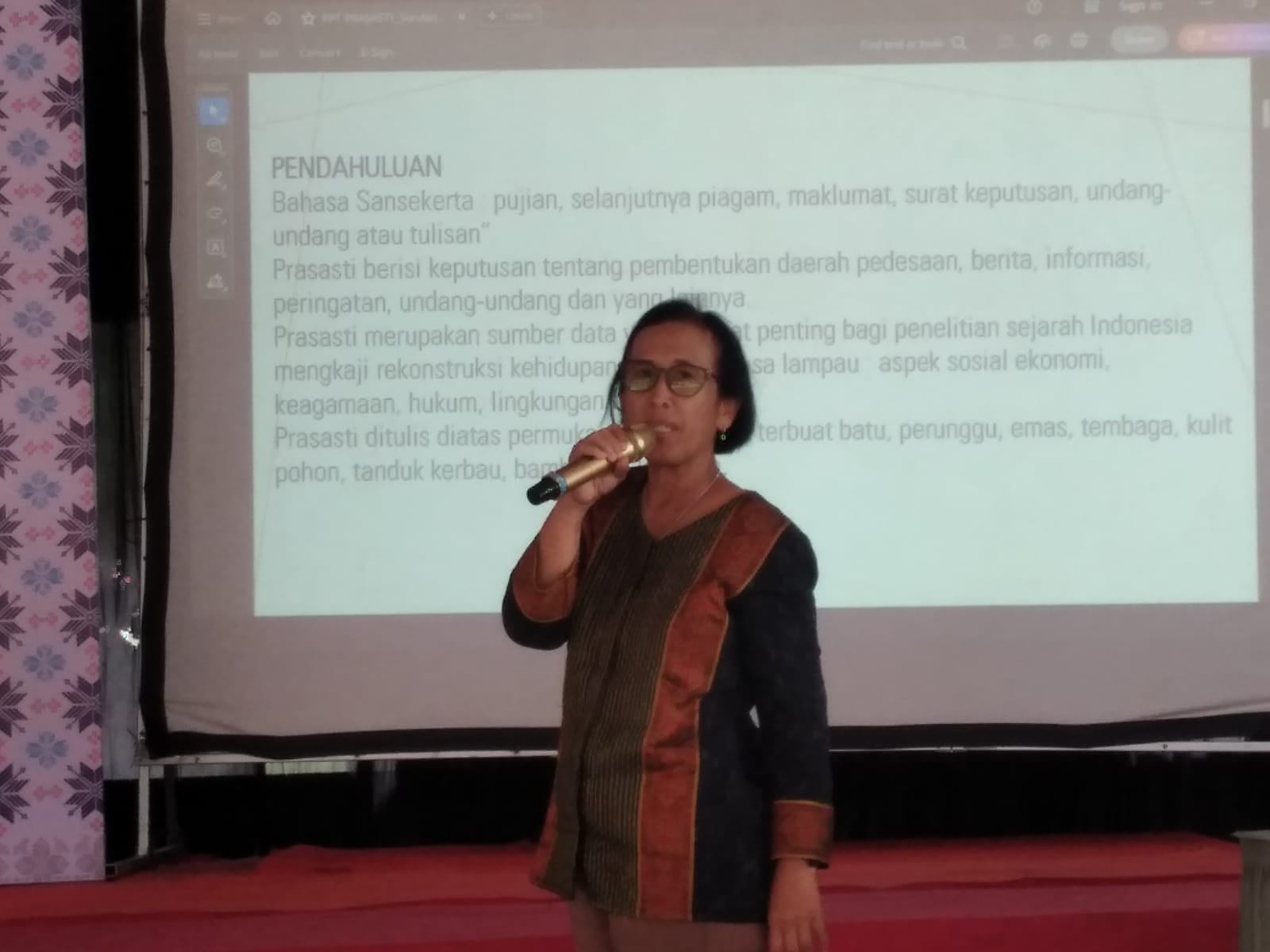
Senada, Arkeolog BRIN, Sondang Martini Siregar, menyoroti alasan mengapa Sriwijaya mengeluarkan banyak prasasti kutukan. Menurutnya, itu adalah bentuk pernyataan otoritas dan kekhawatiran penguasa atas potensi pemberontakan dari daerah-daerah taklukan.
“Prasasti kutukan adalah ekspresi kekuasaan yang tegas. Ia memperlihatkan bagaimana datu menanamkan rasa takut dan loyalitas kepada para pejabat dan rakyat,” ungkapnya.
Sondang menambahkan, kutukan dalam prasasti tidak hanya berlaku pada individu pengkhianat, tetapi juga pada siapa pun yang mendorong, membujuk, atau bekerja sama dalam persekongkolan terhadap kerajaan. Keluarga pelaku pun turut terkena kutuk.
“Ini menunjukkan betapa kuat dan sakralnya sistem otoritas Sriwijaya. Sanksinya tidak hanya bersifat duniawi, tapi juga spiritual, melibatkan sumpah di hadapan para dewa,” ujarnya.

















